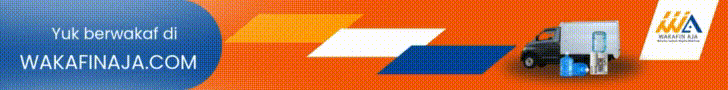Saat Fikih Bertemu Algoritma: Mengapa Kita Masih Butuh Pakar?

Akhir-akhir ini Indonesia dihebohkan dengan kabar kematian seorang mahasiswi asal Mojokerto yang dibunuh secara sadis oleh rekannya sendiri. Jasad korban bahkan dimutilasi hingga menjadi beberapa potongan.
Berita tragis ini, seakan menjadi latar pertanyaan menarik dari salah seorang teman santri penulis:
“Apabila ada jenazah yang sudah tidak utuh karena kecelakaan atau bencana, menurut Syaikh Al-Bakrī al-Dimyāṭī dalam I‘ānah al-Ṭālibīn, selama masih ditemukan jasadnya, maka jenazah tetap wajib dipulasara secara lengkap. Hanya saja, bila memandikannya justru menyebabkan kerusakan baru atau menambah parah kondisinya, maka cukup digantikan dengan tayamum. Pertanyaannya, jika jenazah tersebut sudah hancur luluh atau bahkan hanya tersisa debu, bagaimana cara men-tayamum-kannya? Lalu, jika yang tersisa hanya kepalanya saja, apakah wajib dihadapkan ke kiblat saat dimakamkan? Apakah ukuran menghadap kiblat mayit saat dikebumikan itu sama dengan ukuran menghadap kiblat bagi orang yang sedang salat (yakni dadanya)?”
Karena fokus tulisan ini bukan untuk membahas seluruh pertanyaan di atas, penulis cukupkan dengan menjawab satu di antaranya, yaitu: “Apakah ukuran menghadap kiblat mayit saat dikebumikan itu sama dengan ukuran menghadap kiblat bagi orang yang sedang salat (yakni dadanya)?” Dalam hal ini, penulis mengutip pendapat Imam ar-Ramlī dalam Fatḥ al-Raḥmān yang menyatakan bahwa “wajib menghadapkan wajah jenazah ke arah kiblat.”
Adapun pertanyaan-pertanyaan lain telah penulis jawab melalui percakapan pribadi dengan teman santri penulis tersebut lewat aplikasi WhatsApp, mengingat memang pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan dalam forum obrolan tersebut.
Adapun fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah persoalan yang banyak muncul di kalangan generasi saat ini (Gen Z), yakni apakah masih perlu dan relevan untuk berkonsultasi kepada para pakar—seperti kiai, ulama, atau ustaz—yang memang ahli di bidangnya, terkait pertanyaan-pertanyaan seputar fikih sebagaimana telah disebutkan di atas.
Hal ini menjadi menarik untuk dibicarakan karena pada era kiwari, teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah berkembang pesat dan hadir hampir di seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut, bisa saja dijawab oleh AI dengan cepat, jelas, dan lugas. Sehingga, muncul anggapan bahwa konsultasi kepada para pakar tidak lagi diperlukan, sebab semua dapat diselesaikan dan dijawab dengan mudah tanpa harus keluar rumah.
Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) dan Kelemahannya
Memang, kecerdasan buatan (AI) telah menunjukkan kemajuan luar biasa dalam berbagai bidang, sehingga banyak aspek kehidupan manusia telah disentuh olehnya. Namun, jika AI diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih, tidak dapat dipastikan bahwa jawaban yang diberikan selalu tepat, valid, dan sahih. Hal ini berkaitan dengan cara kerja sistem algoritma yang menjadi dasar AI.
Sejauh pengetahuan penulis tentang sains data, AI bekerja dengan model algoritmik yang dilatih dari miliaran data teks yang sudah ada. Sistem ini tidak menghasilkan jawaban berdasarkan otoritas keilmuan, melainkan dengan mengenali pola-pola dalam data yang dipelajarinya. Artinya, kualitas jawaban sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan dalam proses pelatihan. Data tersebut bisa saja valid, tetapi bisa juga tidak valid. Jika data yang menjadi rujukan kurang valid atau tidak lengkap, maka jawaban yang dihasilkan pun berpotensi kurang valid dan tidak lengkap.
Dengan demikian, jawaban AI pada dasarnya bersifat probabilistik: jika sumber data yang mendasarinya valid, maka besar kemungkinan jawabannya juga valid; jika tidak, maka jawabannya pun tidak dapat dijadikan rujukan yang sahih.
Selain itu, dalam hal pengutipan, kecerdasan buatan (AI) masih memiliki keterbatasan serius. AI sering kali tidak mampu mengutip suatu pernyataan secara tepat sesuai sumber aslinya. Padahal, dalam tradisi keilmuan, pengutipan (citation) bukan sekadar pelengkap teknis, melainkan bentuk penghormatan intelektual sekaligus wujud kejujuran akademik terhadap karya orang lain.
Dengan demikian, pengutipan yang benar merupakan cerminan integritas ilmiah. Maka, patut dipertanyakan: dapatkah disebut jujur apabila seseorang menyandarkan sebuah pernyataan kepada tokoh atau penulis yang sejatinya tidak pernah menyatakannya?