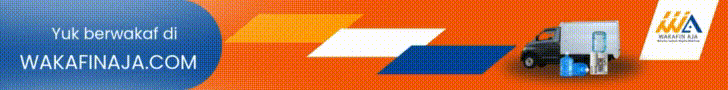Fedi Nuril: Antara ‘Duta Poligami’ dan Mengkritisi Para Petinggi Negeri

Ada sosok yang terus bermetamorfosa di jagat artis Indonesia: Fedrian Nuril a.k.a. Fedi Nuril namanya. Seorang model, aktor, musisi, juga aktivis kemanusiaan pro-Palestina. Dia pernah diinterogasi Tentara Israel saat memasuki Masjid Al Aqsha untuk membuat program acara Ramadan (2014).
Fedi punya julukan yang bisa membuat mak-emak merengut, namun pak-bapak kepincut: “Duta Poligami.” Predikat kocak itu muncul karena dalam beragam film yang dibintanginya–seperti Ayat-Ayat Cinta dan Surga yang Tak Dirindukan— Fedi selalu ketiban peran sebagai suami yang punya lebih dari satu istri.
Untungnya, belum pernah terdengar kabar ada perempuan yang memaki Fedi jika kebetulan bertemu dengannya di jalan. Dalam kehidupan nyata Fedi seorang lelaki ramah, kalem–kecuali jika di panggung sebagai gitaris-kibordis grup alternative rock Garasi yang hingar menggelegar. Dan terutama pada fakta, Fedi suami setia Vanny Widyasasti yang sudah memberinya tiga anak lelaki. Kehidupan pribadi dan keluarganya nyaris tak pernah terekspos ke media massa dalam bingkai ‘bad news is good news’ yang digemari sebagian artis pengungkap aib pribadi.
Namun belakangan ini, Fedi menjadi seorang pencuit yang vokal. Bukan ihwal modeling, akting, atau musik yang dijalaninya, melainkan praktik kekuasaan politik. Siapa pun presiden yang sedang memegang kendali—entah Prabowo atau Jokowi—Fedi tak sungkan mengkritisi.
Bukan hanya kritik terhadap presiden, Fedi juga menulis surat terbuka untuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia mempertanyakan konsistensi Ketua Umum Partai Demokrat itu yang sebelumnya gencar mengkritisi program food estate Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di era Presiden Joko Widodo, namun kritik mendadak hilang ketika diangkat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang pada tahun terakhir masa pemerintahan Jokowi.
Beragam kritik itu berbuah serangan balik dari para pendukung, simpatisan, hingga pendengung (buzzer). Fedi dibuli dan dihujat habis-habisan, namun dia bergeming. Bukan saja kolom komentar Twitternya tak dikunci, Fedi pun menanggapi semua komentar dengan kobaran nyali seorang ronin yang bertempur melawan sekumpulan legiun tentara Shogun.
Saya tak ingin mencuplik twit war antara Fedi dengan lawan-lawannya pada tulisan ini. Pembaca yang tertarik mengetahui bisa membaca langsung pada akun Twitter @realfedinuril untuk mendapatkan gambaran aroma perang argumen yang terjadi di sana.
Saya lebih tertarik melihat fenomena kritik Fedi Nuril sebagai wujud artikulasi dan partipasi publik dalam menjaga potensi penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan, seperti dipostulasikan Lord Acton dalam perkataannya yang masyhur “Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely.”
Dari mana Fedi Nuril mendapatkan energi dalam menyuarakan kritiknya yang berapi-api kepada para petinggi negeri? Setidaknya ada 4 (empat) faktor yang jalin berkelindan dalam pengamatan saya.
Pertama, keberanian patriotik dalam darah Fedi mengalir dari ayahnya, Nuril Rachman, seorang kolonel yang wafat kala Fedi masih kelas 5 SD. Dalam interaksi yang tak terlalu lama itu, “Ayah saya pernah diajari cara mengupas jeruk sunkist oleh Bung Karno,” ungkap Fedi dalam satu cuitannya.
Bisa diduga, sang ayah juga mengisahkan banyak sisi lain tentang sikap patriotisme dan bakti kepada tanah air yang mengendap di relung-relung bawah sadar Fedi kecil. Maka, nasionalisme yang terbentuk dalam jiwa Fedi seiring pertambahan usia dan kematangan jiwa adalah loyalitas kepada bangsa, bukan kepada rezim yang berkuasa, apalagi sosok individual yang sedang berjaya.
Kedua, baik ayah maupun ibu Fedi, Tuty Nuril, sama-sama perantau Minangkabau yang mengadu nasib di Jakarta. Sudah lazim menjadi pengetahuan publik bahwa etnis Minang memiliki standar egaliter yang tinggi, bahkan terhadap para pemimpin. Orang Minang tak terbiasa membungkuk, apalagi menyembah sujud, kepada pimpinan dan atasan. Dalam filsafat kekuasaan Minang, para pemimpin hanya dalam posisi “lebih tinggi sebenang”. Tetap dimuliakan, tetapi tidak ditempatkan sebagai dewa di awang-awang.